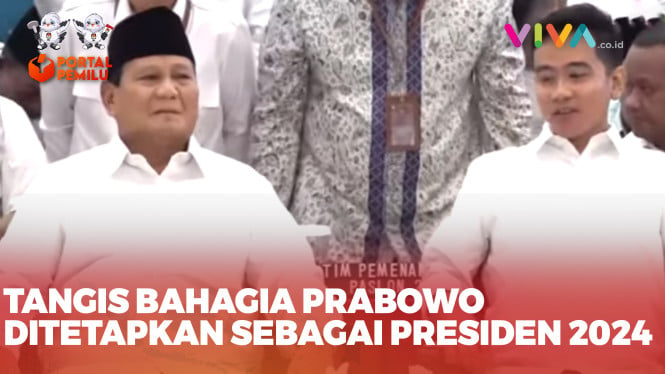Pengantar Redaksi:
Sejak berada dalam tahanan KPK, Andi Mallarangeng punya lebih banyak waktu luang. Sambil menunggu pengadilan, ia mencoba memanfaatkan waktunya secara produktif dengan membaca dan menulis. Aturan KPK tak membolehkan penggunaan laptop, iPad dan semacamnya oleh para tahanan. Andi menulis artikel ini dengan tulisan tangan, dan kemudian disalin kembali oleh Redaksi VIVAnews agar bisa dinikmati oleh pembaca.
---
Kapan seseorang disebut dewasa? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tapi ia memiliki implikasi yang agak rumit dalam dunia hukum dan politik.
Secara biologis, soalnya lebih sederhana. Tanda-tandanya pun jelas. Kalau perempuan, titik awalnya adalah menstruasi. Saat itu tubuh wanita telah memproduksi telur yang siap untuk dibuahi. Kalau laki-laki, ia biasanya diawali dengan peristiwa mimpi basah, yang menjadi sinyal bahwa “pelakunya” sudah siap memproduksi sperma.
Itulah gejala yang sering disebut sebagai masa akil balig atau pubertas, yaitu masa perubahan memasuki usia remaja, untuk kemudian menjadi manusia dewasa. Biasanya, peralihan ini terjadi pada usia 13-16 tahun. Namun, penelitian terbaru memperlihatkan bahwa masa pubertas sekarang ini menjadi semakin dini. Di negara-negara maju, mungkin karena gizi yang lebih baik, tidak jarang menstruasi sudah terjadi pada anak wanita berusia di bawah 10 tahun.
Jika secara biologis persoalan kedewasaan berkisar pada urusan telur dan sperma, secara psikologis soalnya agak sedikit berbeda. Kaum psikolog akan berkata, ukuran kedewasaan tidak semudah itu. Ia lebih berhubungan dengan jiwa dan kematangan pribadi. Seseorang bisa saja berumur tua, tapi kelakuan dan sikapnya masih kekanak-kanakan. Atau sebaliknya.
Para ahli biologi dan psikologi bisa terus berbeda sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sisi politik dan hukum, kerumitan yang ada menjadi berlipat kali.
Urusan hukum harus hitam putih. Garis batas kedewasaan harus jelas dan tidak membingungkan, sebab ia menjadi ukuran bagi seseorang untuk dianggap sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab, serta dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya.
Uniknya, dalam soal hukum dan politik, lain negara lain pula aturannya. Bahkan ada negara yang mengatur garis batas kedewasaan bertingkat-tingkat, sesuai dengan obyek hukum yang diaturnya. Di Amerika Serikat, misalnya, untuk membeli minuman keras, termasuk memasuki bar yang menjual alkohol, seseorang harus berumur 21 tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda pengenal.
Artinya, di negeri Paman Sam ini seseorang baru dianggap mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam hal konsumsi alkohol jika ia sudah berumur 21 tahun. Kurang dari itu, ia dianggap belum dewasa. Makanya, salah satu tonggak umur yang sering dirayakan di AS adalah ulang tahun ke-21, karena saat itu dia bebas masuk ke dalam bar dan memesan bir atau minuman keras lainnya.
Tapi anehnya, dalam politik, ukuran kedewasaan tersebut ditarik lebih rendah, yaitu 18 tahun. Warga AS sudah diberi hak pilih dalam pemilu pada usia tersebut. Rupanya, keputusan untuk meminum segelas bir dianggap membutuhkan tingkat kedewasaan yang lebih ketimbang keputusan untuk memilih seorang presiden atau wakil rakyat.
Indonesia adalah Negara Pancasila. Namun dalam soal kedewasaan berpolitik atau dalam menjadi subyek hukum, kita agaknya lebih liberal ketimbang Amerika. Warga Indonesia sudah diberi hak pilih pada usia 17 tahun. Artinya, entah benar entah tidak, undang-undang yang ada menganggap bahwa kita lebih cepat matang secara politik ketimbang warga AS.
Lebih unik lagi, hak pilih bagi warga Indonesia juga diberikan kepada mereka yang belum berumur 17 tahun, sejauh mereka sudah atau pernah menikah. Sekalipun masih berusia 16 tahun atau lebih muda lagi, sejauh sudah atau pernah menikah, seseorang otomatis bisa ikut memilih dalam pemilu.
“Liberalisme” seperti ini mungkin hanya ada di Indonesia. Pak Jaya Suprana barangkali perlu mempersiapkan rekor MURI dalam kontes pemilih termuda di dunia. Kemungkinan besar pemenangnya akan berasal dari Indonesia.
Dari mana datangnya keunikan tersebut? Ketentuan UU Pemilu yang memberikan hak pilih dengan patokan perkawinan (tanpa memandang usia) sudah ada sejak lama. Ia adalah warisan yang tak lapuk oleh zaman, terus bertahan di era Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Dari mana asal-usulnya?
Penjelasannya panjang. Tapi singkatnya, ia berasal dari tradisi pemilihan kepala desa yang kemudian diadopsi dan dilanggengkan oleh negara. Dalam tradisi desa di Jawa, misalnya, hak suara dalam rembug desa ditentukan berdasarkan posisi seseorang dalam struktur sosial, di mana unsurnya yang terpenting adalah pemilikan tanah. Pada awalnya, para tuan tanah (kuli kenceng) memiliki hak suara, sementara mereka yang tak memiliki tanah (kuli kendo) hanya boleh ikut mendengarkan.
Dalam perkembangannya kemudian, kuli kendo semakin dominan, sebab pemilikan tanah di pedesaan Jawa makin mengecil. Terjadilah pergeseran hak suara dan hak pilih. Ia tidak lagi memakai patokan pemilikan tanah, tetapi status keluarga. Setiap kepala keluarga diberikan hak suara dalam rembug desa. Setiap laki-laki yang sudah kawin, berapapun usianya, otomatis menjadi kepala keluarga dengan hak suara yang penuh. Selain itu, seorang lelaki yang baru kawin memperoleh status sosial baru, yang tak jarang pula diikuti dengan pemberian sebuah nama baru (Paijo menjadi Sutarjo, misalnya).
Itulah asal-usulnya. Tradisi desa yang berkembang di zaman kuda gigit besi terus bertahan dalam berbagai aturan di abad ke-21 ini, dengan implikasi yang besar dalam dunia hukum dan politik kita. Pertanyaannya sekarang adalah, dalam ukuran kedewasaan dan demarkasi waktu sebagai subyek hukum, perlukah semua itu diubah? Jika tidak, apa dampak negatifnya? Saya persilakan para ahli untuk menjawabnya.
Selain itu, ada satu hal lagi yang cukup unik di Indonesia. Di Amerika Serikat, batas minimal usia perkawinan adalah 18 tahun. Kurang sehari dari itu, tidak boleh kawin. Dalam UU Perkawinan kita, batas itu adalah 21 tahun.
Jadi, dalam soal pilihan politik, orang Indonesia dianggap lebih cepat dewasa ketimbang orang Amerika. Tapi dalam soal memilih pasangan hidup, yang terjadi adalah sebaliknya. Orang Indonesia mungkin dianggap terlalu sembrono, atau terlalu mengikuti perasaan saja, dan karenanya harus menunggu agak lama untuk dianggap sebagai individu yang bisa bertanggung jawab penuh dalam soal pembentukan keluarga.
Eh, tapi sebenarnya, peraturan perkawinan kita juga memberi celah yang agak “liberal.” Kenapa? Dalam UU Perkawinan (1974), ada penjelasan bahwa mereka yang belum berusia 21 tahun boleh saja kawin, sejauh mereka memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Indonesia is Indonesia: selalu ada peraturan yang memberi celah dan dispensasi. Asyik, bukan?
Yang jelas, dalam prinsipnya, kita memberi hak kepada para orang tua untuk menentukan kapan anak mereka sudah dipandang dewasa untuk kawin. Artinya, dalam soal ini, kedudukan sebagai subyek hukum lebih menyangkut dimensi subyektifitas dalam hubungan anak dan orang tua, dan karena itulah garis batasnya menjadi agak kabur.
Kekaburan ini membawa masalah tersendiri. Di Amerika Serikat, dari sisi hukum, seorang pria dewasa yang berhubungan badan dengan seorang wanita yang belum berusia 18 tahun akan diperlakukan sebagai seorang pemerkosa. Walaupun hubungan ini dasarnya suka sama suka, hukum tetap menganggap sang pria sebagai pihak yang bersalah (statutory rape).
Di Indonesia, aturan seperti itu tidak jelas. Subyektif. Sang pria selalu bertahan dengan dalih suka sama suka. Jika begini, hukum menemui jalan buntu. Solusinya? Sang pria dan wanita dikawinkan, dengan dalih menutup aib keluarga.
Kepada kaum muda dan remaja kita yang menginjak dewasa, saya ingin sedikit memberi nasehat: peraturan memang agak liberal, tetapi sebaiknya jangan terlalu dimanfaatkan. Sebelum menikah, nikmati dulu masa muda sepenuh-penuhnya. Kedewasaan hanya sebuah istilah. Yang penting adalah pengalaman pribadi dalam mengarungi lautan kehidupan. The more the better.
Dunia begitu luas, kita butuh waktu yang cukup untuk mengerti, meresapi, dan mengambil pelajaran darinya, sebelum pada akhirnya mengikatkan diri dalam bahtera perkawinan. Carpe diem, rebutlah hari ini. Atau dalam istilah gaul sekarang, “yolo” (you only live once). Make the best of it.
Jakarta, 4 Desember 2013
Andi Mallarangeng adalah doktor ilmu politik, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, AS.
Baca Juga Kolom Andi Malarangeng lainnya: